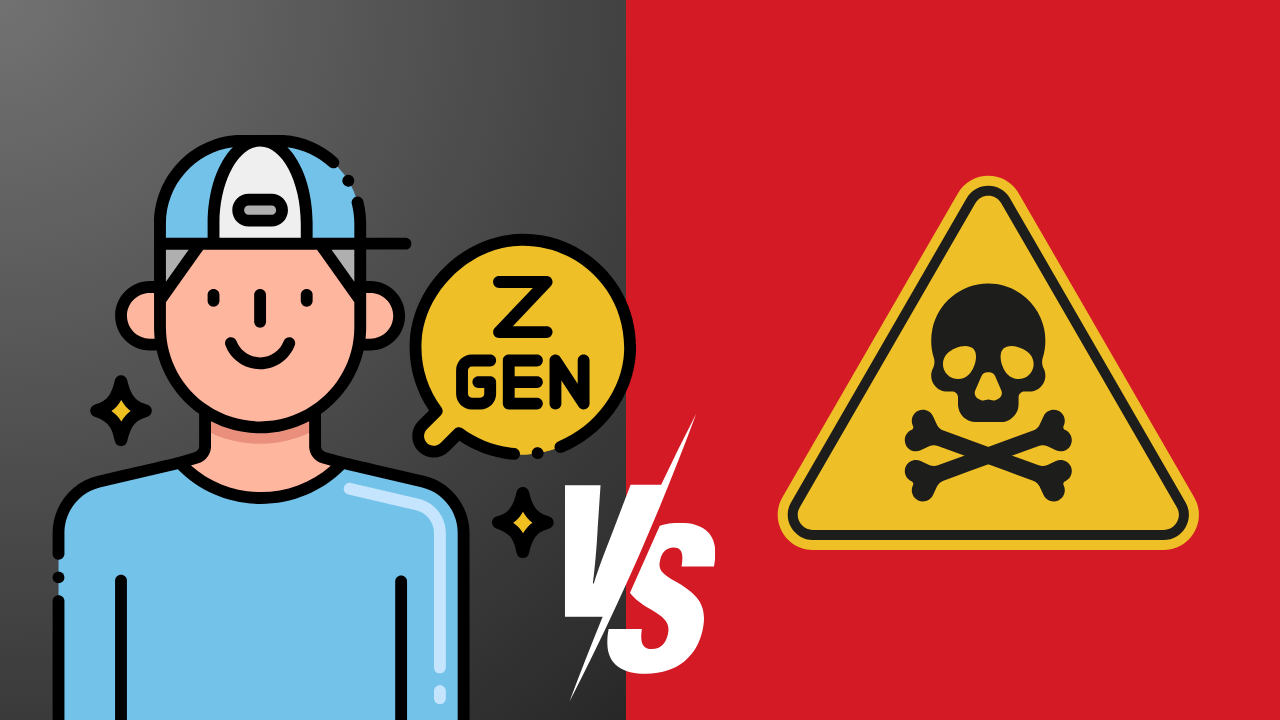
Ketika Positif yang Dipaksakan Justru Bikin Mental Health Gen Z Makin Kacau
“Jangan sedih, selalu bersyukur aja!” atau “Jangan overthinking, kamu harus kuat!” kalimat-kalimat ini mungkin sering Gen Z temui di media sosial, obrolan dengan teman, atau bahkan dari keluarga. Di tengah tren self-care dan mental health awareness, ada fenomena bernama toxic positivity yang diam-diam memperburuk kesehatan mental generasi muda. Apa itu toxic positivity, dan mengapa Gen Z rentan terpapar? Yuk, kupas tuntas!
Toxic Positivity: Positif yang Jadi Bumerang
Toxic positivity adalah kepercayaan bahwa kita harus tetap optimis dan bahagia terus-menerus, bahkan ketika situasi sedang sulit. Alih-alih mengakui emosi negatif seperti sedih, kecewa, atau marah, toxic positivity memaksa kita untuk “move on” atau “lihat sisi baiknya” tanpa validasi yang tulus.
Menurut psikolog Dr. Susan David, penulis buku Emotional Agility, “Toxic positivity adalah bentuk penolakan terhadap pengalaman emosional yang kompleks. Ini seperti mengatakan, ‘Saya hanya mau merasakan setengah dari diri saya’.” (Sumber: TED Talk, The Gift and Power of Emotional Courage).
Gen Z vs. Toxic Positivity: Kenapa Bisa Berbahaya?
Gen Z tumbuh di era media sosial yang penuh dengan highlight reel kehidupan orang lain. Tren meme motivasi, quotes penyemangat, atau konten “good vibes only” sering kali menormalisasi pola pikir bahwa kesedihan adalah aib. Padahal, riset dari University of Melbourne (2020) membuktikan bahwa menekan emosi negatif justru meningkatkan risiko kecemasan dan depresi.
Contoh nyata toxic positivity pada Gen Z:
1. Dipaksa move on setelah putus cinta dengan dalih “cari yang lebih baik”.
2. Dihujam quotes seperti “Masih banyak yang lebih susah darimu” saat curhat tentang tekanan kuliah.
3. Dijauhi karena dianggap “drama queen” saat mengungkapkan kegelisahan akan krisis iklim atau masa depan.
“Tapi Kan Niatnya Baik…”
Benar, banyak orang bermaksud baik saat memberi motivasi. Namun, menurut American Psychological Association (APA), memvalidasi emosi jauh lebih efektif daripada menyangkalnya. Misalnya, alih-alih mengatakan “Jangan menangis”, coba tawarkan dukungan seperti, “Aku di sini untukmu, ceritain saja”.
Seperti yang diungkapkan aktivis mental health Gen Z, Elyse Fox, pendiri komunitas Sad Girls Club:
“Kita tidak perlu menjadi ‘kuat’ setiap saat. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah ruang aman untuk merasa lelah.” (Sumber: Interview dengan Vice, 2019).
Lawan Toxic Positivity dengan Emotional Validation
Berikut cara Gen Z bisa menghindari jebakan toxic positivity:
1. Akuin perasaanmu karena sedih, marah, atau kecewa bukanlah musuh.
2. Unfollow akun medsos yang hanya menjual kebahagiaan instan.
3. Cari komunitas supportif yang mendengarkan tanpa menghakimi
4. Ganti narasi, daripada “Aku harus kuat”, coba “Aku boleh istirahat”.
Gen Z Sudah Mulai Sadar, Tapi…
Data dari survei JWT Intelligence (2021) menunjukkan 68% Gen Z lebih terbuka membicarakan kesehatan mental daripada generasi sebelumnya. Namun, tekanan untuk “tetap produktif” dan budaya hustle di TikTok/Instagram sering kali memicu guilt trip saat mereka ingin beristirahat.
Psikolog klinis Tara Cousineau menegaskan: “Emosi negatif adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mengabaikannya sama saja dengan mematikan alarm kebakaran.” (Sumber: The Kindness Cure, 2018).
Jadi, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Toxic positivity bukan tentang “benci motivasi”, tapi tentang memberi ruang untuk menjadi manusia yang utuh (dengan segala emosi yang ada). Sebagai Gen Z, kita punya kekuatan untuk mengubah narasi:
- Normalize bad days lewat konten kreatif (podcast, TikTok, atau blog).
- Jadi teman yang empatik, dengarkan tanpa buru-buru memberi solusi.
- Edukasi orang sekitar bahwa “tidak baik-baik saja” itu wajar.
Sumber:
1. David, S. (2017). Emotional Agility.
2. University of Melbourne (2020). The Impact of Emotion Suppression on Mental Health.
3. American Psychological Association (APA). The Value of Emotional Validation.




