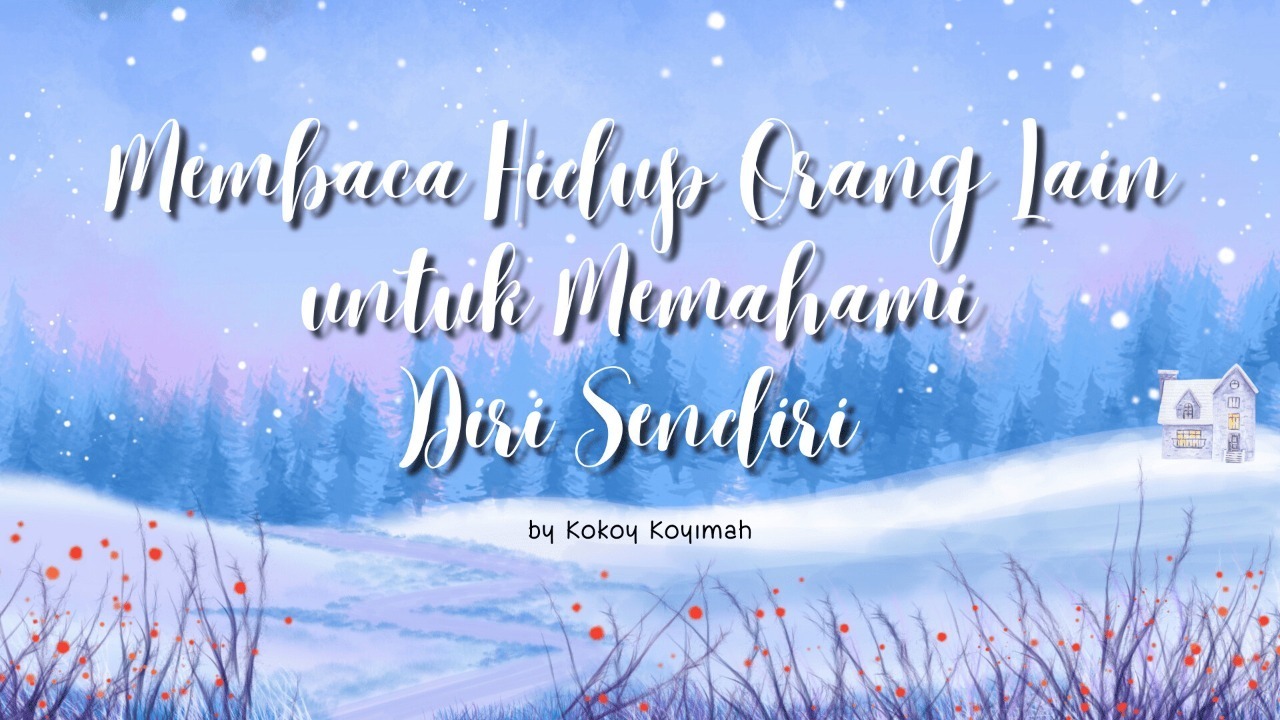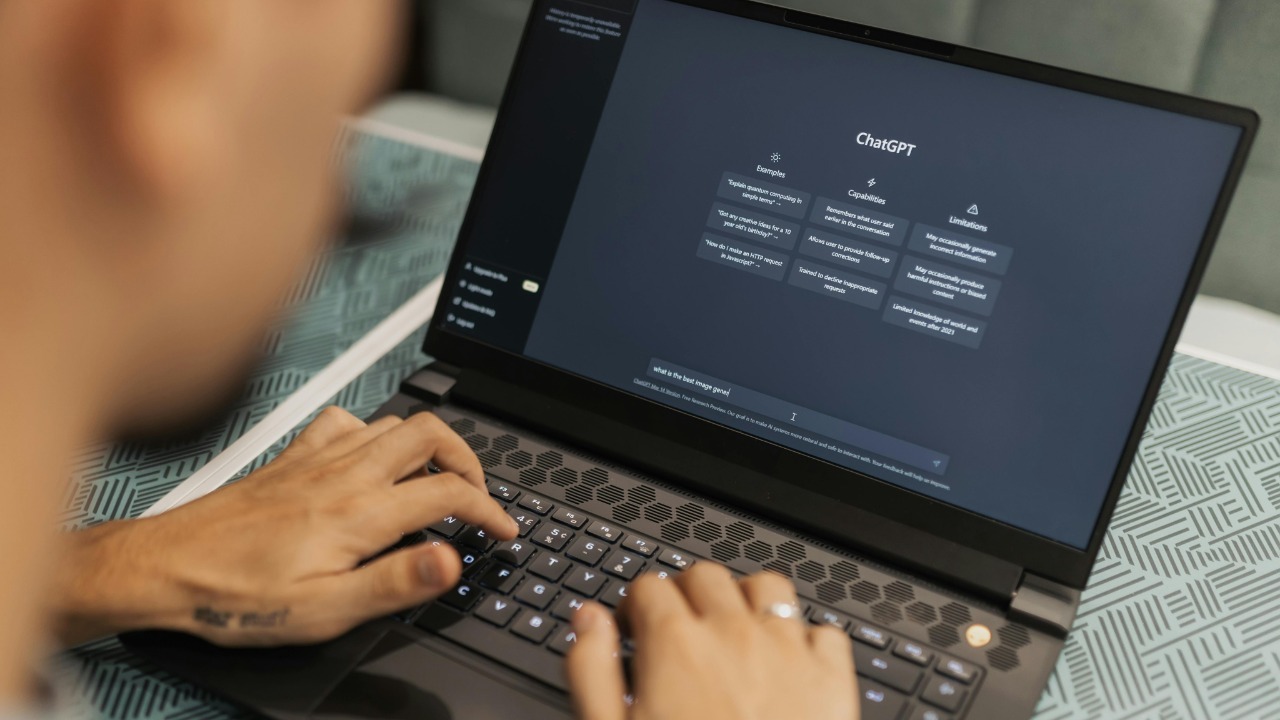Saat Bekerja Menjadi ‘Candu’ Baru
Dalam karyanya yang berjudul “A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right” yang terbit pada tahun 1844, seorang pemikir dan jurnalis asal Jerman yang terkenal, Karl Marx, pernah menulis sebuah kalimat kontroversial, “Agama adalah candu.” Jika saja ia hidup di masa kini, mungkin ia akan merevisi kalimatnya menjadi “Bekerja adalah candu.” Karena di zaman ini, rasa bersalah bukan lagi muncul karena meninggalkan ibadah, melainkan karena berani untuk beristirahat.
Jika anda termasuk orang yang sering scrolling media sosial seperti saya, seharusnya anda sudah tidak asing lagi dengan nama Instagram Influencers seperti Andrew Tate, atau mungkin versi lokalnya seperti Timothy Ronald dan Kalimasada yang selalu mengatakan bahwa anda tidak akan pernah kaya jika anda tidak bekerja keras. Terdengar masuk akal bukan? Kalimatnya yang kasar seolah menjadi cambuk bagi generasi muda yang dianggap ‘malas’ di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Gelombang PHK dimana-mana, mata uang yang semakin melemah dan harga barang-barang yang selalu naik tiap tahunnya, kondisi tersebut membuat nasehat tadi masuk akal, jika kita ingin kaya dan sukses seperti mereka, maka bekerja dengan keras setiap harinya adalah sebuah keharusan. Maka tak heran jika anda melihat banyak sekali anak muda, sebut saja mahasiswa masa kini seperti punya ‘candu’ dalam bekerja, mereka tak segan untuk mengambil dua, tiga atau empat pekerjaan paruh waktu, atau bahkan pekerjaan penuh waktu sekaligus. Faktanya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di berbagai belahan dunia, mereka menyebut ini sebagai fenomena hustle culture.
Hustle Culture atau Grind Culture adalah sebuah istilah yang menggambarkan budaya kerja yang keras, dimana kita perlu mendedikasikan sebagian besar waktu kita untuk pekerjaan dengan bekerja sekeras-kerasnya. Banyak orang yang menganut hustle culture berpandangan bahwa mengalami tekanan, penderitaan dan pengorbanan atas hal-hal pribadi adalah hal yang lumrah untuk mencapai sebuah kesuksesan, maka, berhenti bekerja untuk beristirahat sejenak, berubah dari hal yang menyenangkan menjadi hal yang terasa salah. Karena di mata masyarakat, orang yang bekerja sangat keras dipandang sebagai sesuatu yang baik, bahkan dalam lagu pop masa lalu seperti yang dinyanyikan oleh Koes Plus, terdapat istilah seperti ‘Kerja keras bagai kuda’ yang menggambarkan bahwa sebenarnya fenomena ini bukan cuma terjadi di masa kini, tetapi juga di masa lalu. Karena budaya ini sebenarnya mempunyai arti yang sama dengan workaholic, yaitu orang yang tak bisa berhenti bekerja, hanya saja istilah modern ini terdengar lebih keren dan positif setelah sering sekali digunakan oleh influencers media sosial masa kini untuk menjustifikasi budaya ini.
Hustle culture memiliki manfaat dalam membentuk etos kerja generasi muda. Mengingat Indonesia merupakan negara yang akan mengalami surplus masyarakat produktif yang disebut dengan bonus demografi pada tahun 2030, meningkatnya tren bekerja keras di kalangan generasi muda, menjadi salah satu hal yang dianggap dapat mendongkrak produktivitas kerja dan ekonomi dalam masyarakat. Budaya ini juga membantu generasi muda tetap keep-up atau sejalan dengan dunia masa kini yang semakin tak pasti, tak ayal banyak generasi muda seperti mahasiswa masa kini berpandangan bahwa budaya ini membantu mereka untuk berkembang, bahkan sebagian beranggapan bahwa budaya ini juga membantu mereka untuk melawan narasi negatif tentang Gen-Z yang dianggap sebagai generasi stroberi, mudah lelah dan tak tahan banting. Namun di sisi lain, semangat untuk terus bekerja sering kali lahir bukan dari dorongan murni untuk berkembang, melainkan dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial membuat segalanya tampak kompetitif, seolah kesuksesan orang lain adalah kegagalan pribadi. Dari situlah tekanan untuk selalu produktif muncul, hingga tanpa sadar kita sudah masuk dan terjebak dalam siklus hustle culture.
Dalam budaya ini, sulit sekali bagi kita untuk membagi diri, karena saking kerasnya kita bekerja, secara tak sadar, kita tidak bisa membagi diri antara kehidupan pekerjaan profesional dan kehidupan pribadi. Fenomena ini lumrah ditemukan di kalangan mahasiswa masa kini, dimana banyak diantara mereka yang mengikuti rapat hingga tengah malam, bekerja saat waktunya untuk istirahat atau bahkan menerima suruhan pekerjaan dari atasan saat di luar jam kerja. Hal ini semakin mengaburkan batas-batas (boundaries) kehidupan yang berimplikasi pada buruknya kesehatan mental mahasiswa masa kini. Dalam sebuah penelitian berjudul “The Effect of Hustle Culture on Psychological Distress with Self Compassion as Moderating Variable” yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Lampung dan Universitas Gadjah Mada, disebutkan bahwa hustle culture mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental masyarakat. Dalam penelitian tersebut, rasa cemas (anxiety) yang berlebihan, gugup dan kelelahan mental (burnout) adalah beberapa dampak nyata budaya ini terhadap kesehatan mental. Menariknya, walaupun sebagian besar responden menyatakan bahwa hustle culture ini memiliki dampak negatif, sekitar 66,67% atau sekitar ? responden berpandangan bahwa budaya ini tetap diperlukan, terutama oleh generasi muda untuk mencapai kesuksesan di tengah sistem dunia yang semakin kapitalistik.
Meski memiliki dampak negatif yang tak main-main, ini tidak berarti budaya ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Setiap orang sebenarnya memiliki ruang kendali untuk menata ulang bagaimana cara mereka memandang kerja dan kesuksesan. Hal terpenting yang bisa kita lakukan sebenarnya hanya terletak pada kesadaran diri untuk menetapkan batas-batas (boundaries) yang sehat antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi. Kita perlu belajar membaca sinyal tubuh diri sendiri, memberi izin kepada diri kita yang lelah untuk berhenti tanpa rasa bersalah serta menyadari bahwa nilai seorang manusia tidak diukur dari seberapa sibuk ia terlihat, melainkan dari seberapa bermakna hidup yang dijalaninya. Belajar untuk mengendalikan diri dalam bekerja adalah salah satu cara agar kita bisa tetap ambisius tanpa kehilangan kemanusiaan. Karena mungkin saja, kita tidak perlu menyingkirkan ambisi kita sama sekali, tetapi kita hanya perlu melakukannya dengan cara yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih manusiawi.
(Foto: Stanley Morales/Pexels)
Referensi
Aliya, H. (2025, Juni 11). Hustle culture: Definisi, penyebab, dampak, dan cara menghindarinya. Glints. https://glints.com/id/lowongan/hustle-culture-adalah/
Pertiwi, D. K. (2017, Agustus 3). Memaknai (lagi) ‘Agama adalah Candu’ milik Marx. IndoPROGRESS. https://indoprogress.com/2017/08/memaknai-lagi-agama-adalah-candu-milik-marx/
Yuningsih, Mardiana, N., Jima, H., & Prasetya, M. D. (2023). The effect of hustle culture on psychological distress with self-compassion as moderating variable. In R. Perdana et al. (Eds.), Proceedings of the ULICoSS 2022 (pp. 1062–1073). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_102
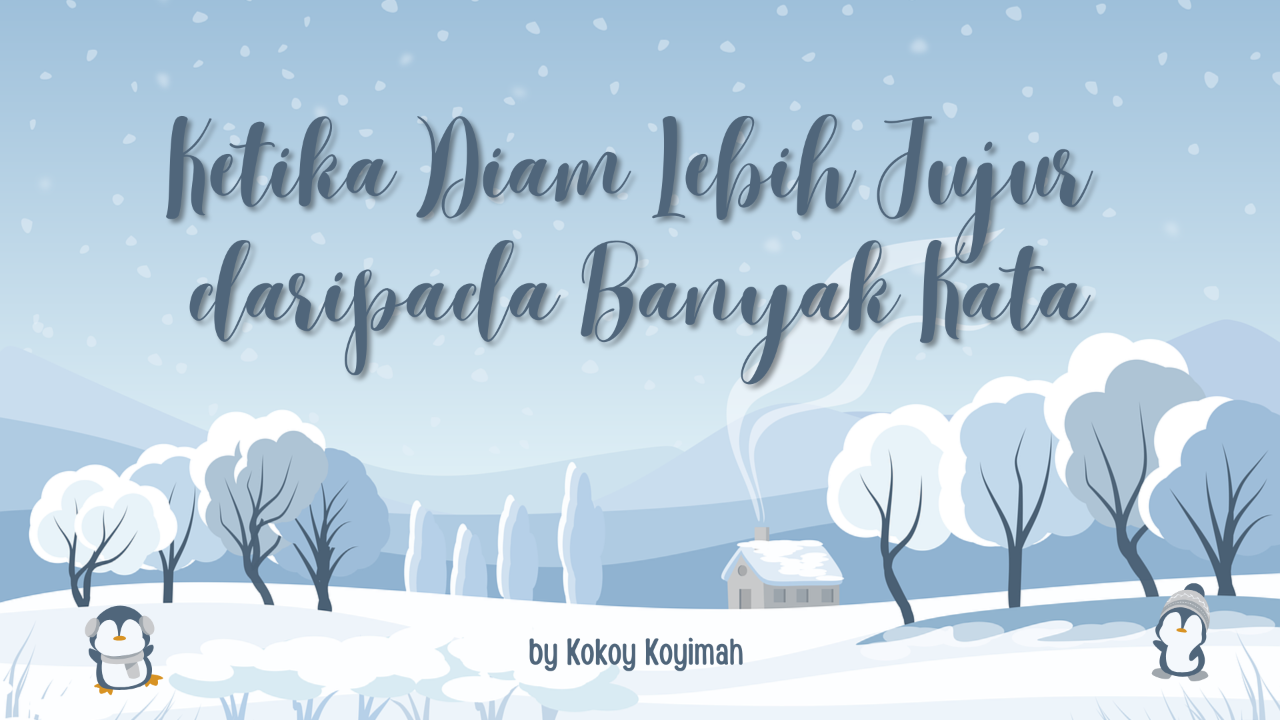
previous post
Ketika Diam Lebih Jujur daripada Banyak Kata