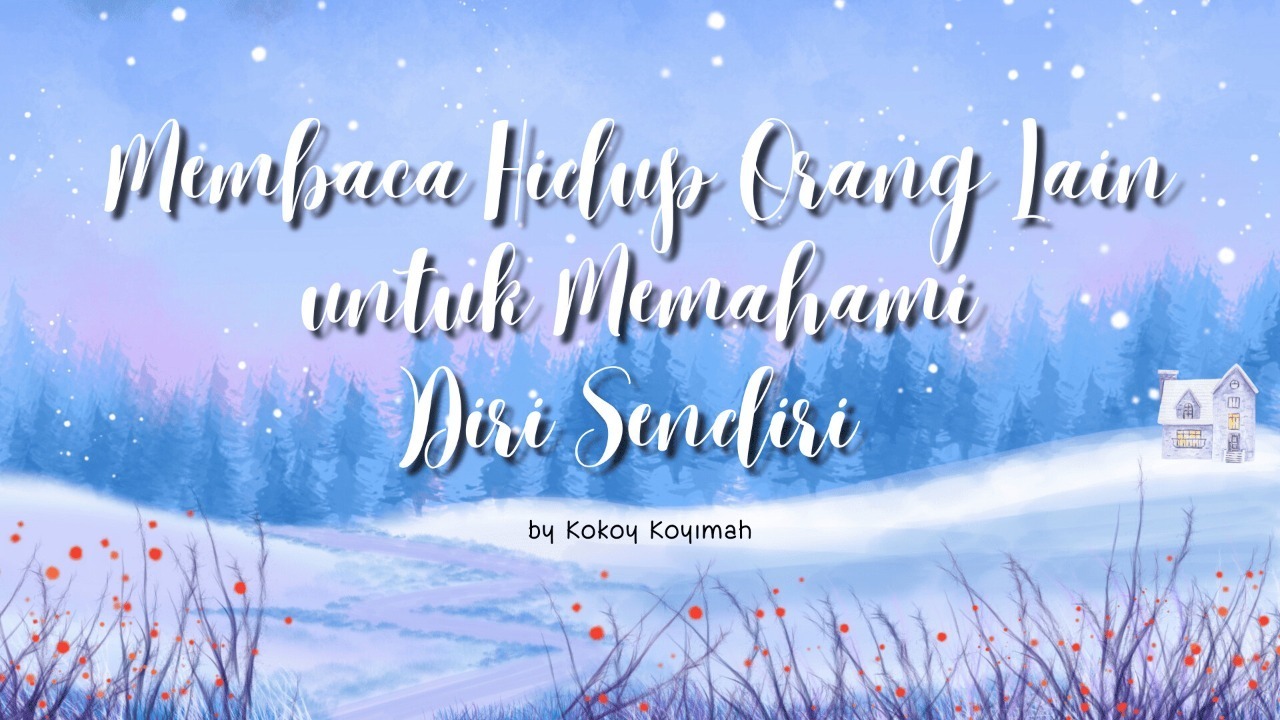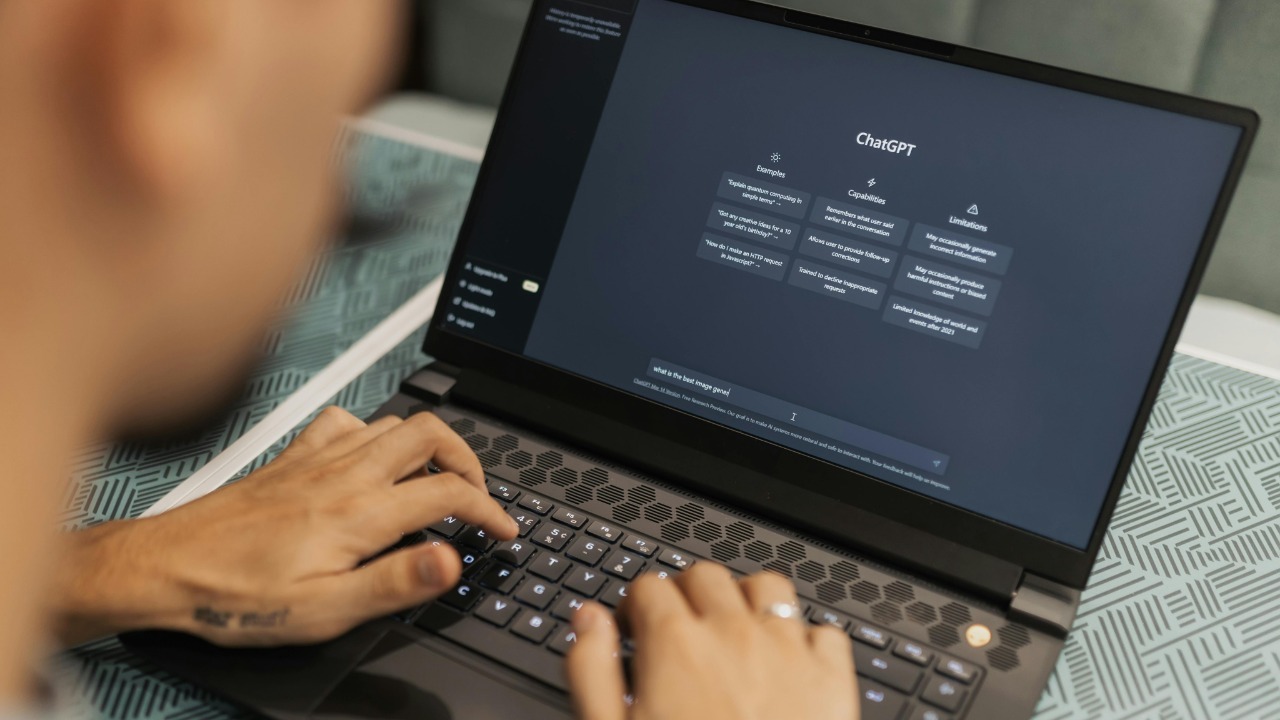TRANSPARANSI KUALITAS ASN TERHADAP RAKYAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
Praktik birokrasi di Indonesia cukup buruk. Adanya pungutan liar; perilaku aparatur sipil negara (ASN) yang tidak sopan, diskriminatif; kurang ramah, sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit, serta tidak menjamin kepastian (waktu maupun biaya) merupakan beberapa contoh akibat kurangnya transparansi birokrasi, khususnya dalam hal pelayanan publik. Sedangkan kualitas berhubungan dengan tingkat kepuasan masyarakat mengenai kemampuan aparatur negara melakukan suatu hal (menyangkut kebijakan publik) secara efektif dan efisien. Akhir-akhir ini, publik menyoroti kasus Pinangki Sirna Malasari, terdakwa kasus penerimaan suap 450 ribu dolar AS dari Djoko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali¬. Pinangki melakukan suap agar Mahkamah Agung tak mengeksekusi fatwa yang telah dijatuhkan. Selain itu, bersama Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya diduga melakukan permufakatan jahat sebab berjanji memberikan 10 juta dolar AS pada pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung bila fatwa yang dimaksud tidak terlaksana. Pasal selanjutnya yang didakwakan adalah pencucian uang, karena uang suap tersebut diduga digunakan untuk membeli BMW X-5, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat, menyewa apartemen di New York, membayar tagihan kartu kredit, dan menyewa dua apartemen di Jakarta Selatan. Awalnya ia dijatuhi vonis 10 (sepuluh) tahun penjara, lalu dikurangi menjadi 4 (empat) tahun penjara. Selain itu, jjaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus Pinangki juga tidak mengajukan kasasi atas pemotongan hukuman Pinangki Sirna Malasari, karena tuntutan telah dipenuhi dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tidak hanya itu, Pinangki (selanjutnya disebut demikian) statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)—hingga saat ini—‘hanya’ diberhentikan sementara, sebab vonis pengadilan belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). Di Indonesia, kasus korupsi sering sekali menjadi ‘menu’ sehari-hari. Hal ini tidak mengherankan, sebab menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2020 terdapat 1.298 terdakwa; dengan rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 21 kasus, pihak swasta dengan jumlah 286 kasus, dan (terakhir) perangkat desa sebesar 330 kasus. Akibat tindak pidana itu, ICW juga melaporkan kerugian negara mencapai 56,7 triliun )—total kerugian negara indak pidana suap sejumlah 322,2 miliar rupiah. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti yang ditetapkan untuk terdakwa hanya sebesar 19,6 triliun rupiah—total nilai denda hanya sebesar 156 miliar rupiah. Ini berarti bahwa uang negara yang masuk kembali ke kas hanya sekitar 12-13 persen. Hal tersebut sebetulnya masih perkiraan, sebab hingga saat ini ICW masih menunggu data resmi dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara umum, faktor yang menyebabkan pelaku melakukan korupsi antara lain: 1. Pendidikan ‘dasar’ seperti agama, moral, dan etika kurang ditanamkan sejak dini sehingga cenderung lemah; 2. Sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi belum ada dan tidak nampak secara kontekstual; 3. Pengawasan kebijakan yang sifatnya efektif dan efisien sangat lemah; serta 4. Sistem pemerintahan yang cenderung tidak menganut sistem terbuka (transparan). Adapun akibat dari tindakan korupsi terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Dampak terhadap negara Tindak pidana korupsi sangat berdampak di berbagai sisi, sehingga mengganggu antara satu dan lainnya; mulai dari keuangan negara hingga menghambat pembangunan nasional. 2. Akibat bagi individu Seseorang yang terkena kasus korupsi, terlebih lagi seorang ASN, selain sanksi pidana dan pemecatan di instansi tempatnya bertugas; dalam masyarakat ia akan menerima sanksi sosial dengan diberi label ‘koruptor’. Sedangkan kendala bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS bagi pelaku korupsi adalah: 1. Sulitnya mendapat salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah); 2. Putusan telah dijatuhkan tetapi oleh yang bersangkutan putusan tersebut digugat dan akhirnya dimenangkan atau dikabulkan; 3. Putusan bellum dijatuhkan oleh PPK, sebab PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) telah pensiun berdasarkan Batas Usia Pensiun (BUP)—58 tahun untuk pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan, lalu bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya adalah 60 (enam puluh) tahun; 4. PPK tidak menjatuhkan sanksi tersebut dikarenakan yang bersangkutan adalah PNS yang mutasi dari instansi lain, sedangkan instansi asal tidak menyampaikan data atau salinan putusan pengadilan yang bersangkutan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pada intinya, fokus utama pencegahan korupsi, khususnya di Indonesia, adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Selain itu kedua hal ini juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap negara. Beberapa tantangan penegakan hukum dan reformasi birokrasi antara lain: 1. Koordinasi aparat, khususnya dalam pertukaran informasi dan data antar-lembaga penegak hukum belum optimal; 2. Modus kejahatan yang semakin berkembang dan ‘rumit’ di era digital tidak disertai dengan penguatan adaptasi proses penegakan hukum; 3. Maraknya ‘penyelewengan’ dalam penegakan hukum; 4. Inspektorat pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dinilai masih lemah dalam hal independesi, pengawasan, serta pengendalian internal pemerintah; 5. Kualitas keterbukaan informasi belum merata; ditambah dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan layanan publik yang rendah; sehingga membuat pengawasan sistem kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang (seharusnya) diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi (disebut sistem merit) berjalan tidak optimal; dan 6. Pengawasan pembangunan dan pemanfaatan program belum terintegrasi dengan baik. Faktor kualitas (kecakapan) yang belum optimal menjadi alasan penyelenggaraan birokrasi di Indonesia belum memadai, sebab faktor ini (meliputi kompetensi serta integritas) yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dari internal aparatur—sesuai dengan peran dan fungsi ASN sebagai aktor penting dalam menjalankan sistem pemerintahan (birokrasi) di Indonesia. Kebutuhan akan informasi yang terus meningkat di era teknologi ini, membuat ASN harus memiliki keterampilan berupa literasi media (media literacy) dalam mengakses, menganalisa serta menyebarkan informasi berdasarkan fakta dan terbukti benar (faktual) agar tidak menimbulkan dampak negatif. Selain itu, seorang ASN juga harus memiliki keterampilan dalam menggunakan, memahami serta menilai teknologi yang digunakan (technological literacy) sebagai media dalam melaksanakan program-program pemerintah. Selain hal tersebut, seorang ASN juga harus memiliki beberapa keahlian demi menunjang kebutuhan karir dan lingkungan kerja, seperti fleksibel (cakap bekerja dengan berbagai individu atau kelompok, serta situasi yang berbeda—memahami dan menghargai pandangan yang berbeda dan bertentangan mengenai suatu isu, menyesuaikan sudut pandang karena suatu perubahan situasi, serta menerima perubahan dalam organisasinya); dan adaptif (mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di tempat tugas dan akrab dengan situasi tersebut). Sementara itu, upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yakni: 1. Melakukan pembinaan agama, moral, dan etika; dengan cara memberikan penyuluhan agama, moral, etika, dan hukum di instansi tempat bertugas. 2. Memberi sanksi yang berefek jera terhadap pelaku korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Fungsi pengawasan di pusat atau daerah (bergantung tempat tugasnya) oleh inspektorat perlu ditingkatkan agar kepala daerah tidak ikut campur tangan ketika ada temuan kasus korupsi. 4. Komitmen seluruh instansi pusat atau daerah untuk menciptakan lingkup kerja aparat yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. DAFTAR REFERENSI Achmad, S. Ruky. 2003. Kualitas Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Briantika, Adi. 2021. “Kasus Djoko Tjandra & Mengapa Jaksa Pinangki Harus Divonis 20 Tahun”, ed. Rio Apinino. Tirto.ID. 1 Februari. https://tirto.id/kasus-djoko-tjandra-mengapa-jaksa-pinangki-harus-divonis-20-tahun-f9Lr. (4 Juli 2021). Guritno. Tatang. 2021. “ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun”, ed. Diamanty Meiliana. Kompas.com. 9 April. https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567 (5 Juli 2021). _____________. 2021. “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun”. Kompas.com. 22 Maret. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp (5 Juli 2021). Hariyoso, S. 2002. Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Peradaban.
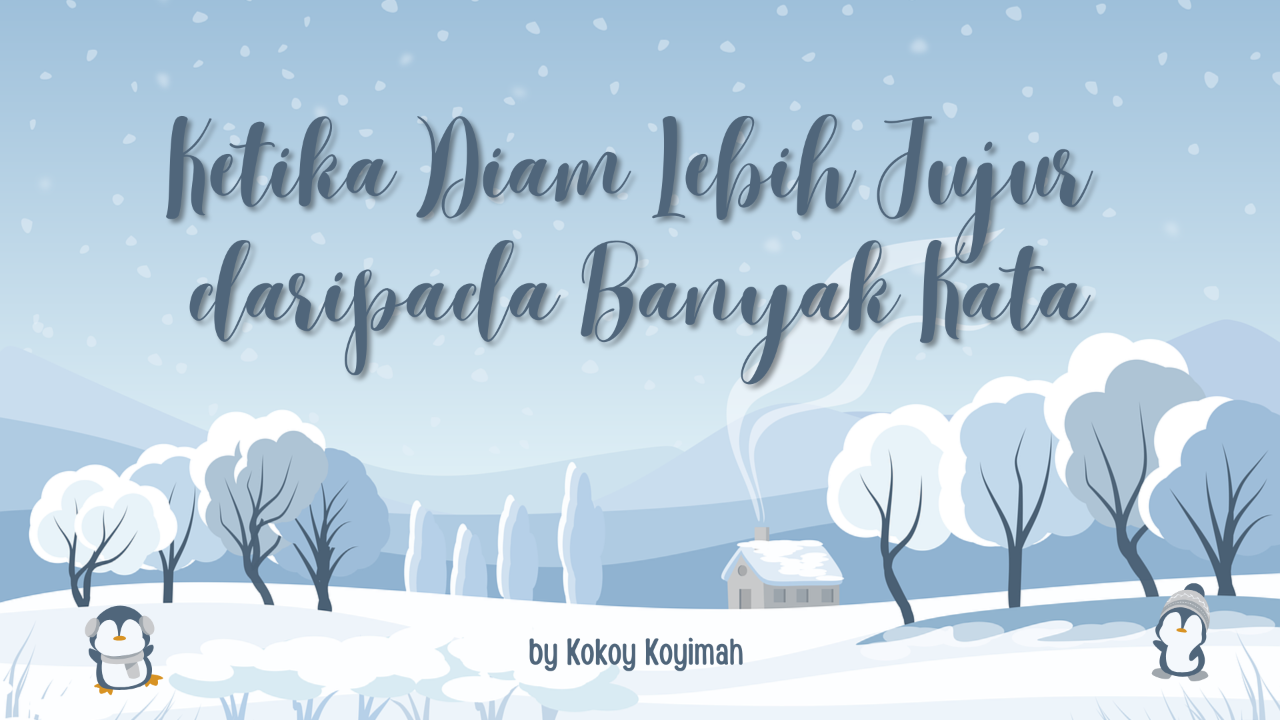
previous post
Ketika Diam Lebih Jujur daripada Banyak Kata